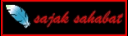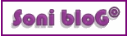Raungan hewan-hewan besi sudah memekak sejak fajar menyingsing. Mengisi
jalur aspal dengan kebisingan, kesemrawutan dan kepadatan. Mentari tentu cerah
pagi itu, karena tidak pernah mentari cerah pada malam hari. Jalan yang berdiri
di udara bak akan runtuh ketika para pengendara kendaraan berkendara diatasnya,
getaran beton dan pekikan klakson sudah menjadi menu sarapan setiap pagi bagi
mereka yang mengistirahatkan hidup bersama naungan jembatan. Udara segar khas
buangan sisa pembakaran fosil tentu lebih cepat terasa ketimbang semua hal
tadi. Tak sebanding dengan apa yang diberikan oleh makhluk hijau yang seakan
tak memiliki hak hidup disana.
Bagi sebagian mereka yang baru dan belumlah terbiasa, atau bahkan yang
selalu merasakan, maka semuanya sudah seperti neraka. Entah bagaimana mereka
berpikir, tapi hanya dengan melihat apa yang mereka rasakan, mereka bisa bisa
saja mengatakan itu neraka. Tapi itu tak berlaku bagi Sena, bocah kecil lusuh
ini sangat antusias, tak peduli pagi itu cerah, mendung, hujan, sejuk bahkan
terik sekalipun. Senyum dan semangat selalu ia kobarkan dalam hati dan
gerakannya.
Apakah tidak terasa olehnya bahwa sekelilingnya hanyalah perkampungan
kumuh dibawah jembatan? Apa keindahannya? Apa kelayakannya? Bocah kecil itu
menatap pantulan wajahnya pada sebuah pecahan cermin yang sudah tergores gores.
Senyum ia lukiskan sebelum meletakkan cermin pada kotak kayu bekas. Ia berjalan
kearah seorang perempuan tua yang duduk bersimpuh, menggerus rotan yang nanti
akan dijual, tidak banyak laba memang, paling tidak bisa membantu menjaga perut
agar tidak kelaparan. Ia menabik wanita tua itu, dengan memohon restu dan ridho
akan apa yang ia kerjakan. Ya, wanita itulah satu satunya manusia yang bisa ia
cintai dari relung hati, tak ada yang lain. Niat tulus adalah dasar
semangatnya, melangkah meninggalkan wanita tua itu menuju keluar dari naungan
jembatan.