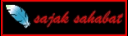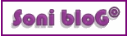“Sudahkah kepantasan dalam takdir
hadir padamu?”
Pertanyaan itu, pertanyaan yang
mengiang-ngiang di kupingku setiap kali melihat wujud harapan dan doa yang
kupintakan menari-nari dalam tudung sutra yang melingkupinya. Aku tidak pernah
ragu, tidak pula mengingkari kekhawatiran, namun bayang-bayangnya adalah
idam-idaman sanubari yang senantiasa membisikkan asa.
Di depanku dirimu bergerak,
berpindah dari satu pijakan ke pijakan lainnya dengan gemulai anggun yang
mungkin nilainya tiada dapat terukur. Setiap kakimu memijak bumi, netramu
memandang sesuatu dan mengabaikan acuhanku. Asyik bersenandung dengan orang
yang memberikan sesuatu yang masih belum mampu kuhadirkan untukmu. Aku hanya
melihat abai, menikmati berbagai adegan dalam rangkaian detik yang menggilas,
menunggu hingga tiba waktu yang seharusnya datang.
Di suatu hari yang muram, saat suara
riangmu menerimanya dengan gempita, aku bertanya pada seseorang yang mungkin
empunya akan sesuatu yang tidak tampak oleh mata, dan tak terasa oleh akal.
Pertanyaan yang penuh keresahan, memancar dari kedua bola mataku yang
menatapnya dengan suram.
“Lepaskanlah nak. Lepaskan. Jika
tangan mereka yang meraih bukanlah tangan yang suci, waktu akan membawanya
pergi untukmu,” kata Si Empu Tua dengan suara yang sudah melemah termakan usia.
Aku tidak menjawab langsung.
Menghela beberapa hirupan napas kemudian aku berkata kepadanya, “akankah
kubiarkan kedua mataku menjadi saksi?”
Si Empu Tua itu tidak lagi menjawab
dengan lisan. Ia berjalan mendekatiku, menepukkan kedua tangannya yang keriput
ke bahuku. Berlalu pergi, meninggalkan aku yang sedang dinaung rasa nestapa.
Dengan kalbu yang pudar, kusisiri
jalan setapak yang terbentuk di tengah padang ilalang. Di bawah langit mendung yang
kelabu, aku berjalan lurus tanpa benar-benar tahu apa yang ada di depan, bagai
menjaring keputusasaan. Batang demi batang ilalang yang kulewati patah oleh
petikan tangan, walau kubuang petikan itu tanpa menggali manfaatnya.
Terus berjalan, lelah dan penat
mendekatiku. Mengajakku untuk mampir sebentar, alih-alih terus berjalan tak
tentu arah. Aku tidak memaksa, kuturuti keinginan mereka dan menyelonjorkan
kaki sambil bersandar di batang sebuah beringin. Aku duduk di atas salah satu
akar besarnya yang terpampang ke permukaan tanah. Pohon beringin ini sangat
rimbun, hanya titik kecil cahaya yang sanggup melewati kerindangan dedaunannya.
Pawana yang lembut menyapu-nyapu di
wajahku. Sejuk lembutnya mengobati kepenatan yang menjamur di otot-otot tubuh,
lama-kelamaan mendatangkan kantuk yang ingin membawaku pergi ke dunia
angan-angan. Sekejap aku sempat berpikir, ‘bukankah dunia angan-angan itu lebih
indah?’
Belum sampai tiga detik rasanya aku
memejamkan mata, sesosok perempuan dengan rambut tergerai telah berdiri di
sampingku. Wajahnya ramah, senyum membentang dan matanya memandang penuh binar.
“Hai,” katanya kepadaku.
“Ha, hai,” jawabku terbata. Aku baru
saja melompat beberapa desimeter menjauhinya karena rasa kaget yang luar biasa.
“Ada apa gerangan engkau kemari?”
tanyanya, masih dengan senyum terbentang.
“Tidak ada apa-apa selain melepaskan
keriuhan penat. Adakah keberadaanku mengusikmu?” tanyaku dengan sedikit segan
dan ekspresi memohon maaf.
“Tentu saja tidak. Teruskanlah. Aku
tidak akan mengganggumu,” jawabnya. Wajahnya masih menampilkan senyum.
Perempuan ini masih muda, kurasa.
Wajahnya belum terlalu dimakan usia, mungkin baru saja melewati masa remaja dan
kalaupun ia adalah wanita yang lambat penuaannya, usianya pasti belumlah
terlampau jauh. Paling-paling sebaya denganku. Kulitnya bersih meski pakaiannya
kumal, gerai rambutnya tidak beraturan tapi hitam cantik. Kakinya tidak
beralas, memijak bumi.
“Duduklah, mari bercerita sebentar,”
tangan kanannya menunjuk kembali akar tempatku duduk tadi. Isyarat memperkenankan.
-----
Ia begitu santun kepadaku. Segelas
air dan ramah tamah lainnya begitu mengena. Menyampaikan siratan bahwasanya ia
adalah sosok yang ramah dan bisa diajak berteman serta mungkin saja menjadi
empu dalam berbagai masalah pribadi.
“Siapa namamu?” tanyaku padanya.
Ia tersenyum dan memandang jauh ke
padang ilalang yang tadi kutempuh. “Kau boleh menamaiku apa saja. Silahkan,”
Aku mengangguk-angguk saja meski
rasa heran menggerayangi sanubari. Biarlah, mungkin itu haknya, dan aku
bukanlah siapa-siapa selain seseorang yang baru saja berada di dekatnya.
“Kulihat, engkau begitu cemburu,” ia
bertanya kepadaku sambil tertawa terkikik.
Daripada tawa yang terkikik itu, aku
lebih menaruh perhatian kepada kalimatnya. Aku tidak tahu bagaimana cara menjawabnya,
bahkan tak tahu apa yang ia tanyakan. Tidak mengerti, diam saja.
Selama beberapa saat kami senyap
bersama. Aku tidak bergerak sedikitpun dengan mata yang tertuju pada padang
ilalang yang rimbun. Banyak hal yang kurasakan, nelangsa, nestapa tapi tidak
tahu apakah yang ia tanyakan tadi juga ada kurasakan. Terik sang surya
menghujami rimbun ilalang, sedang hati
dipayungi kontras yang sendu.
Dari kejauhan kulihat tiga orang,
mungkin lelaki, mendekat. Mereka berjalan dengan risih akan ilalang di sisi
mereka. Raut wajah mereka tampak tidak menyenangi sesuatu, barangkali waspada
dan siaga atau penuh ketakutan? Entahlah. Aku bukan pembaca raut wajah.
Kuabaikan saja meski arah penglihatan kepada mereka.
“Andai engkau boleh cemburu, engkau
mau?” Ia bertanya lagi kepadaku. Lagi-lagi kalimat itu. Sungguh enggan aku
menjawab, meski akhirnya menjadi segan.
“Tidak apa-apa. Tidak usah engkau
jawab. Jangan pernah putus asa, ya! Jangan seperti mereka, yang datang kepadaku
tanpa cahaya dan mengakhiri waktu dengan tatapan putus asa. Lihatlah ilalang
itu, meski terkadang dipotong dan dicabuti, ia tetap tumbuh dan tak
peduli. Ia hanya menyerahkan nasibnya kepada Yang Esa.”
Ia diam sebentar, kemudian melanjutkan, “waktu akan memberimu sesuatu yang semestinya
untukmu.”
Aku mendengar dan menyimak, tapi
tidak menjawab dan memerhatikannya. Aku masih fokus memandangi tiga orang
lelaki yang kini sudah semakin dekat. Semakin dekat jarak, semakin bergegas
langkah mereka.
“Kenapa engkau di sini? Pulanglah!”
ucap salah seorang dari mereka, dan dua orang lagi hanya berdiam diri dan
gemetar.
Aku diam meski heran. Mereka
terlihat tidak senang. Aku tahu bahwa sudah saatnya pergi, daripada orang-orang
ini menjadi semakin durja. Aku berpaling ke samping, hendak berpamitan dan
berterimakasih atas jamuan singkat yang disuguhkan. Namun, belum sempat
berucap, perempuan tadi telah tiada. Tidak terlihat tanda-tandanya, bahkan
bekasnya pergi. Aku memutar badan dan mengerjapkan mata, tapi nihil.
Ketiga orang pria yang “mengusirku”
itu memberi isyarat agar aku cepat pergi. Aku tidak banyak menjawab,
kuanggukkan kepala dan kaki kulangkahkan ke arah padang ilalang. Menyusuri
jalan pulang, kembali dalam kehidupan rutin. Sejenak, kusadari ketiga orang laki-laki
tadi menggeleng-gelengkan kepala ke arahku, seolah tidak habis pikir melihat
keberadaanku.